Sepertinya definisi mengenai ACEH yang A berarti Arab, C berarti Cina, E berarti Eropa dan H berarti Hindia sudah sangat familiar di telinga kita. Saya pribadi pada saat masih duduk di sekolah dasar sering memikirkan hal demikian, jika orang Aceh benar campuran dari keempat kebudayaan besar dunia ini, maka saya merupakan bagian yang mana? Namun setelah itu saya nyerah untuk memikirkan hal seperti itu. Dalam buku ini akhirnya saya menemukan jawaban yang lebih mandalam. Budaya banyak dipahami dengan artian berbeda yang kian dipaparkan satu persatu dalam buku ini, namun singkatnya dapat kita mengerti bahwa budaya merupakan hasil pemikiran manusia yang dipraktekkan di dalam kehidupan mereka.
Membahas tentang budaya Aceh mungkin sangat luas, pada bab ini akan difokuskan saja pada perkembangan budaya Aceh dan bagaimana kita memahami Budaya Aceh. Jika dilihat masa lalu “endatu” orang Aceh maka dalam bab ini penulis menukilkan lagu Rafly yang berjudul Hoka Raja Loen, disini tampak dengan jelas bahwa asal keturunan bangsa Aceh adalah dari Persia. Adapun dalam karya Affan Jamuda dan A.B.Lila wangsa yang berjudul Peungajaran Peuturi Droe Keudroe disebutkan begini penggalannya dalam terjemahan Indonesia “bangsa Aceh adalah satu bangsa yang membangun negeri di sebelah barat Pulau Ruja. Bangsa ini asalanya dari bangsa Acemenia, bangsa Achemenis berasal dari sebuah bukit Kaukasus di Eropa Tengah….” Beberapa sumber yang dipaparkan dalam bab ini juga merujuk kepada asal usul endatu Aceh dari Persia. Namun, yang menariknya dari dulu hingga sekarang beberapa sumber yang dijelaskan dalam bab ini juga mengatakan bahwa Aceh milik atau tanah para Wali Allah.
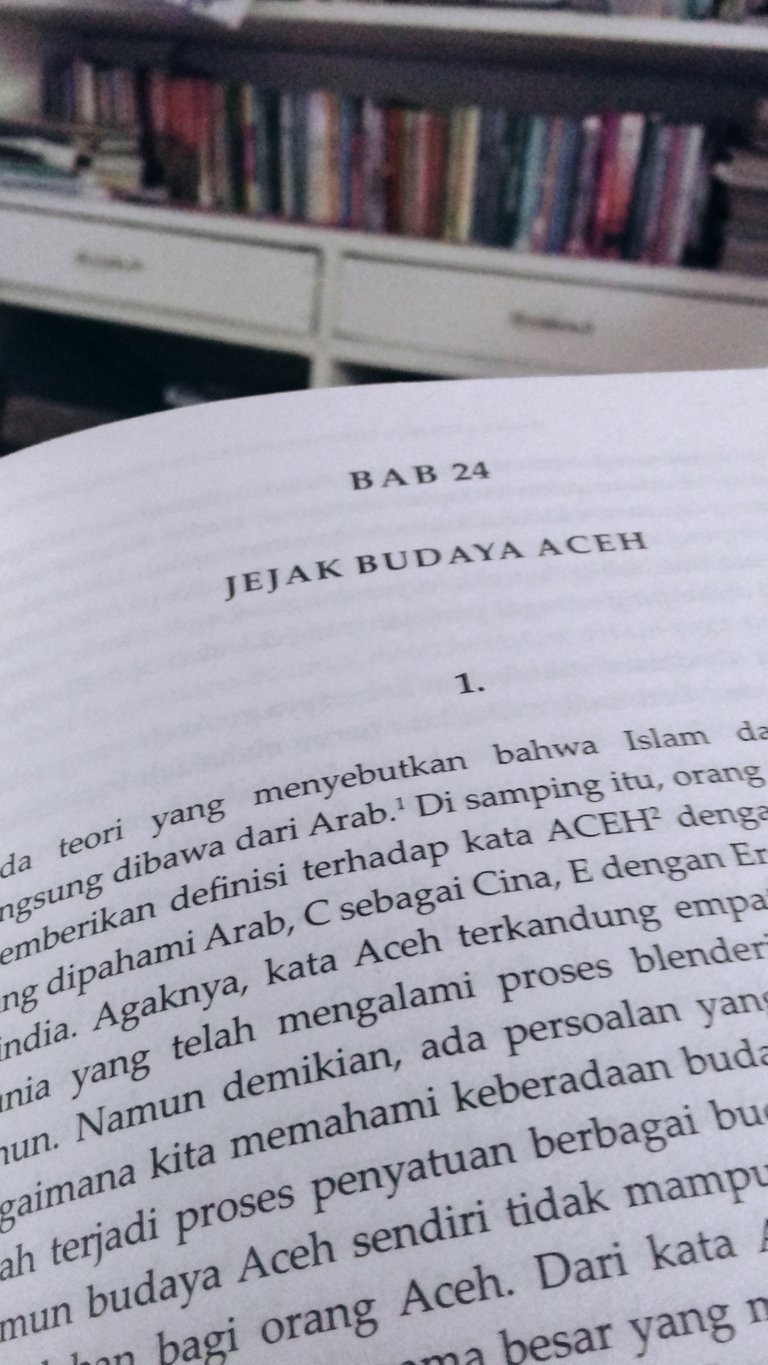
Adapun, mengenai aturan kehidupan di dalam masyarakat rakyat Aveh memang hamper serupa dengan rakyat Jawa, hanya saja sejak proses islamisasi tata aturan kehidupan rakyat Aceh lebih banyak diwarnai oleh Islam. Namun, pada situasi tertentu pengaruh budaya Hindu dan Buddha masih dijumpai hingga hari ini (hal.794). Untuk urusan hukum, disimbolkan dengan istilah “Syiah Kuala” simbol bermakna Ulama, adapun persoalan tata laksana lebih didasarkan pada simbol “Po Teumeureuhom” yang bermakna Raja atau yang punya kekuasaan, untuk persoalan cara berfikir dan cara kemajuan masyarakat disimbolkan dengan “Reusam ban bentara”, dan untuk persoalan upacara-upacara yang bersifat kerakyatan namun disitu ada simbol budaya maka dikenal dengan istilah “qanun bak putroe phang”. Disini, Putri Pahang disimbolkan sebagai tokoh wanita.
Dalam persoalan mistik atau Gaib, seperti orang Jawa, orang Aceh juga percaya adanya hal tersebut, masyarakat Aceh sangat yakin adanya makhluk gaib yang sering diistilahkan dengan burong (hantu), teu meugu (dimasuki roh jahat saat berada di tempat tertentu), teu mamong (kesurupan), peukeunong (santet), meusihe (belajar ilmu sihir) meutapa (bertapa atau bersemedi). Namun demikian semua aktivitas di atas, kecuali yang berbau sihir, selalu dibingkai dengan ritual keislaman yaitu do’a (meu do’a) (hal.799).
Beberapa tradisi yang percaya dengan Alam juga ada dilakukan di Aceh, seperti keunduri laot dengan menyembelih kerbau, bentuk syukur terhadap pemberian laut sebagai nafkah. Keunduri Blang, merupakan bentuk memohon keberkaham kepada sang maha Kuasa sebelum turun ke sawah. Kuburan yang menjadi pusat kosmis, dimana dijumpai masyarakat Aceh masih sering menziarahi makam-makan keuramat yaitu makam ulama untuk melangsungkan nazarnya,dan sebagainya. Namun segala hal tersebut tetap dalam bingkai meu-do’a menurut ajaran Islam.
Memahami konteks kebudayaan Aceh, bagaimana kita memahami apa yang dipikirkan orang Aceh tentang hidup mereka. Kita juga perlu mengkaji proses mistik dalam kehidupan orang Aceh disini supaya dapat melihat dimana Aceh dan Islam “berpisah” di dalam kehidupan masyarakat Aceh, serta dimana Islam bersatu bagi kepentingan orang Aceh. Melihat bagaimana cara orang Aceh mengetahui keberadaan mereka dengan Alam yang selama ratusan tahun mampu menjaganya, dan dari sini dapat kita temukan sebenarnya bagaimana hasil berfikir orang Aceh dileburkan dalam bingkai budaya.

